Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)
Pulau Obi seharusnya menjadi simbol kejayaan nikel Indonesia. Tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan wajah paling brutal dari industrialisasi. Listrik mati-hidup di rumah warga, air bersih yang menghilang, dan kampung-kampung pesisir yang dibiarkan gelap, haus, dan tak berdaya.
Peristiwa boikot warga Kawasi terhadap aktivitas Harita yang berlangsung hampir sepanjang hari dan menutup operasional perusahaan membuktikan bahwa yang terjadi bukan hanya gangguan layanan, tetapi krisis sosial-ekologis yang lahir dari ketimpangan relasi kuasa.
Hal ini bukan lagi soal anomali, tetapi penghinaan terhadap martabat manusia. Di kawasan industri Harita Group, tungku smelter menyala tanpa jeda. Lampu-lampu pabrik menyinari langit malam Obi seperti kota industri raksasa. Energi melimpah, air mengalir deras, mesin beroperasi dalam ritme kapital yang tidak pernah tidur.
Tetapi hanya beberapa ratus meter dari pusat industri itu, warga Kawasi menghadapi kenyataan yang memalukan. Listrik tak stabil, air bersih yang hanya hadir sebagai janji, dan debu industri yang menyelimuti rumah-rumah. Bahkan penyakit infeksi pernapasan dilaporkan meningkat pada anak dan lansia.
Kampung yang berada di “ring satu tambang” justru menerima layanan yang tidak layak disebut layanan dasar. Padahal ada kesepakatan tertulis antara warga dan perusahaan untuk menyediakan listrik dan air ditandatangani tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak Perusahaan namun tidak kunjung diwujudkan. Inilah pola klasik dalam ekonomi politik ekologi di mana keuntungan dikonsentrasikan di pusat produksi, sementara biaya sosial-ekologis dilempar kepada masyarakat lokal.
Lebih gila lagi, kondisi listrik dan air yang memburuk ini muncul bersamaan dengan wacana relokasi paksa. Warga menunjukkan pola yang mencurigakan. Layanan dasar melorot, tekanan naik, dan iming-iming pindah ke “pemukiman baru” terus digulirkan. Jika benar kondisi ini sengaja dibiarkan membusuk untuk mendorong warga angkat kaki, maka yang terjadi bukan Pembangunan tetapi rekayasa penderitaan.
Industri nikel yang dijanjikan sebagai masa depan energi hijau justru menciptakan ketidakadilan paling kotor di wilayah pengorbanannya. Konstruksi “energi hijau” di tingkat global ternyata bisa bertumpu pada praktik yang sangat tidak hijau di tingkat lokal.
Pencemaran lingkungan (ekosistem), krisis air, hilangnya ruang hidup, dan munculnya konflik antara warga, perusahaan, dan aparat seolah menjadi fenomena biasa. Pulau Obi menjadi arena ujian paling telanjang tentang bagaimana industrialisasi bisa mengorbankan komunitas pesisir sebagai “tumbal pembangunan”.
Perusahaan bisa berkelit lewat laporan CSR yang rapi dan foto-foto seremonial, tetapi orang kampung tidak hidup dari laporan. Mereka hidup dari listrik yang menyala, air yang mengalir, laut yang bersih, dan ruang hidup yang aman. Dan semua itu sedang terkikis, digusur, dan dipinggirkan. Boikot yang dilakukan warga Kawasi adalah bentuk adaptasi sosial terakhir ketika saluran atau canal respons formal – dialog, musyawarah, laporan ke pemerintah tidak lagi dipercaya.
Saat industri menikmati terang, warga dipaksa menerima gelap. Saat pabrik memperoleh pasokan air stabil, warga harus membeli atau mengangkut sendiri. Ketika keuntungan berlipat, hak dasar masyarakat justru melorot. Dalam perspektif sistem sosial-ekologis, ini adalah tanda bahwa kapasitas adaptif masyarakat ditekan sementara beban ekologis justru meningkat.
Di titik ini pembangunan yang memadamkan kampung adalah pembangunan yang gagal sejak awal. Pulau kecil seperti Obi bukan ruang tanpa penghuni yang bisa dikorbankan untuk ambisi industri. Warga berhak hidup layak tanpa harus menjadi korban sampingan dari rakusnya mesin ekonomi.
Jika pemerintah dan perusahaan terus menutup mata, maka Pulau Obi akan tercatat sebagai contoh paling gamblang tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan merampas hak dasar dan martabat masyarakatnya.
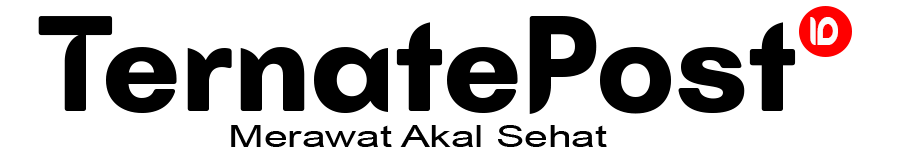














Tinggalkan Balasan