Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)
Jika pesisir adalah halaman depan rumah Maluku Utara, maka tambang yang tidak diawasi adalah api di teras, dan negara berdiri menonton sambil berkata: nanti kita hitung kerugiannya.
Blokade warga Sagea menandai lebih dari sekadar resistensi terhadap satu korporasi tambang; ia mengekspresikan kritik terhadap lemahnya pemenuhan kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat pesisir.
Penyebutan Sagea sebagai “benteng terakhir” dapat dipahami sebagai penilaian sosial-ekologis atas rapuhnya tata kelola sumber daya alam di Maluku Utara.
Situasi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara laju ekspansi ekstraktif dan perangkat pengawasan, antara keberanian praktik di lapangan dan daya paksa hukum, serta antara dominasi kepentingan industri dan pengakuan atas hak warga pesisir.
Persoalan ini perlu dibaca secara jernih dan proporsional. Yang dipersoalkan warga tidak berhenti pada aktivitas tambang, tetapi menyasar cara negara memberi izin, melakukan pengawasan, serta membiarkan kegiatan berlangsung tanpa kontrol yang memadai.
Dugaan beroperasinya perusahaan tanpa dokumen kunci seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila terbukti, menunjukkan cacat tata kelola yang serius, bukan kekeliruan administratif yang remeh.
RKAB berfungsi sebagai perangkat kendali yang mengikat aspek teknis, ekonomi, dan kepatuhan pelaporan; ketiadaannya membuat pengawasan kehilangan landasan operasional yang kuat.
Lebih rawan lagi, keluhan warga terkait penimbunan dan reklamasi pesisir memperlihatkan bagaimana pesisir terus diperlakukan sebagai ruang sisa untuk kepentingan industri.
Padahal pesisir Teluk Weda merupakan ruang hidup utama nelayan kecil, habitat biota perairan dangkal, sekaligus sistem penyangga ekologis yang rapuh. Dampak kerusakan di wilayah seperti ini tidak menunggu kajian bertahun-tahun untuk terasa.
Ia hadir segera melalui air yang keruh, rusaknya habitat dangkal, jarak melaut yang semakin jauh, biaya yang meningkat, dan hasil tangkap yang menurun.
Pola tersebut bukan peristiwa tunggal. Ia berulang di berbagai titik pesisir Maluku Utara, termasuk Weda, Buli, dan Obi, ketika ekspansi industri nikel berjalan beriringan dengan meningkatnya kerentanan masyarakat pesisir.
Hilirisasi kerap dipromosikan sebagai kemajuan, tetapi yang lebih cepat tiba di kampung nelayan sering berupa ketidakpastian nafkah dan ketegangan sosial akibat perubahan ruang hidup dan kualitas lingkungan.
Dalam situasi seperti ini, tawaran ganti rugi sering digunakan sebagai jalan pintas penyelesaian. Namun narasi tersebut menyimpan masalah konseptual dan etis, karena ia menggeser isu dari hak atas lingkungan yang sehat menjadi soal harga dan transaksi.
Ruang hidup, situs budaya, serta sistem nafkah tidak layak direduksi menjadi angka kompensasi. Kerangka hukum dan tata kelola lingkungan menempatkan pencegahan dan kehati-hatian sebagai prinsip yang harus didahulukan, bukan kompensasi setelah kerusakan terjadi.
Kasus Sagea juga menampakkan persoalan klasik dalam praktik negara, yakni fragmentasi kewenangan. Ketika pengawasan laut berada pada level tertentu dan sungai pada level lain, pertanggungjawaban atas dampak kumulatif di teluk menjadi kabur.
Celah ini membuat warga berhadapan dengan birokrasi yang saling melempar tanggung jawab. Dalam kondisi saluran formal yang buntu, aksi kolektif warga seperti blokade, protes, dan perlawanan simbolik menjadi mekanisme koreksi terakhir. Menyalahkan warga tanpa membenahi sistem hanya memperdalam pengingkaran tanggung jawab negara.
Karena itu, respons yang dibutuhkan bukan kriminalisasi atau pembingkaian warga sebagai penghambat pembangunan. Yang mendesak ialah audit kepatuhan yang terbuka dan independen, dengan membuka status izin, dokumen lingkungan, peta kegiatan, serta hasil pemantauan RKL–RPL kepada publik.
Jika ditemukan pelanggaran, negara berkewajiban menghentikan sementara kegiatan, memastikan pemulihan lingkungan, dan menjamin partisipasi bermakna masyarakat pesisir dalam setiap keputusan.
Sagea pada akhirnya bukan “benteng terakhir” dalam pengertian romantik, tetapi cermin yang memantulkan wajah tata kelola sumber daya alam kita hari ini. Jika negara memilih untuk tidak bercermin, konflik serupa akan berulang di teluk-teluk lain Maluku Utara.
Pembangunan yang mengorbankan pesisir tidak dapat disebut kemajuan; ia adalah akumulasi utang ekologis dan sosial yang kelak ditagih melalui krisis yang lebih besar. Dan negara seharusnya memilih lebih awas, waras dan tegas dari sekarang jika tidak ingin kehilangan legitimasi dari warganya sendiri.***
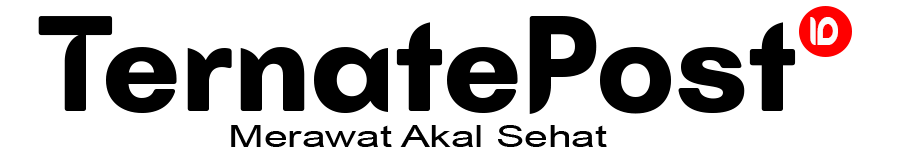

















Tinggalkan Balasan